Sulawesi Tenggara – Pencemaran laut di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), akibat limbah tambang nikel membuat Maria kian sulit mendapatkan penghasilan. Perempuan 51 tahun itu kini hanya menggantungkan hidup dari membelah ikan dan memperbaiki pukat.
Kesulitan Maria memperoleh peluang ekonomi akibat pencemaran laut membuatnya terjebak dalam kemiskinan. Dia tercatat dalam 213 keluarga miskin berdasarkan profil Desa Baliara tahun 2022. “Kenapa saya begini Tuhan?” tanya Maria merenungi nasibnya sendiri, Senin, 10 Maret 2025.
Pencemaran laut di Baliara terjadi seiring masifnya penambangan nikel yang dilakukan PT Timah Investasi Mineral (TIM), anak usaha PT Timah Tbk., dan PT Trias Jaya Agung (TJA). Padahal Maria sudah menggantungkan sebagian besar hidupnya di laut. Maria juga merupakan satu dari 1.442 jiwa masyarakat di Baliara yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
Bagi masyarakat suku Bajo sepertinya, melaut merupakan budaya, di samping memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal serupa dialami petani rumput laut di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Sejak PT Billy Indonesia (BI) melakukan eksploitasi nikel di Torobulu tahun 2010, petani berhenti total memproduksi rumput laut.
Masyarakat sempat membudidayakan kembali rumput laut setelah PT BI angkat kaki pada 2016. Sialnya, sejak 2019, pengganti PT BI, PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), masif beroperasi seiring kebijakan hilirisasi nikel yang digalakkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, aktivitas tambang nikel di Torobulu kian masif.
Kembalinya aktivitas penambangan nikel lagi-lagi menghilangkan mata pencaharian petani rumput laut di pesisir Torobulu. Menurut warga Torobulu, Kamaruddin, perusahaan nikel merupakan biang keladi rusaknya rumput laut di desanya. Kamaruddin punya pengalaman ketika kembali mencoba membudidayakan rumput laut pada 2022.
Tahun itu, Kamaruddin sempat membudidayakan rumput laut dengan modal awal Rp1 juta, tetapi rugi total. Tanah dari galian perusahaan tambang nikel mengalir ke laut. Air yang sudah tercemar lalu mengenai rumput laut. Proses itu menyebabkan rumput laut tak berkembang, bahkan menjadi rontok dari talinya dan mati. “Tanah merah turun dari atas. Kapan kena rumput laut, langsung putih, patah-patah, habis, tidak ada sisa,” jelas Kamaruddin, Kamis, 28 Februari 2024.
Ketua Kelompok Tani Lowania, Arifin, juga sudah lama resah dengan air bercampur lumpur dari bekas galian tambang nikel yang masuk ke sawahnya di Desa Okooko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Arifin menyebut padi yang terkena aliran air bercampur lumpur menjadi kerdil, anakan berkurang, dan warnanya kekuningan. “Ini dia contohnya,” kata Arifin menunjuk petak sawah yang berada di sisi aliran irigasi, Rabu, 19 Maret 2025.
Air irigasi Arifin dan petani lainnya bersumber dari Sungai Okooko yang membelah Kecamatan Pomalaa dan Tanggetada. Sepanjang sungai yang melewati Desa Okooko dan Lamedai, warnanya kuning kecokelatan. Air kuning kecokelatan berasal dari tanah bekas galian tambang di sepanjang Sungai Okooko. “Dampaknya ini luar biasa. Bukan main-main dampaknya tambang terhadap pertanian,” ungkap Arifin.
Kerusakan lingkungan telah mengganggu bahkan menghilangkan mata pencaharian masyarakat lokal di luar sektor pertambangan nikel. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan kian sulit untuk produktif, menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan penghasilan. Di Baliara, tercatat 213 keluarga miskin dari total 401 kepala keluarga berdasarkan profil desa tahun 2022.
Angka itu menunjukkan lebih dari setengah penduduk Baliara merupakan keluarga miskin. Sama halnya di Torobulu. Berdasarkan profil desa tahun 2024, sebanyak 420 kepada keluarga di Torobulu masuk dalam kategori prasejahtera. Jumlah itu hampir setengah dari total penduduk Torobulu yang berjumlah 450 kepala keluarga.
Sementara di Okooko, keluarga prasejahtera berjumlah tiga kepala keluarga dari 428 kepala keluarga pada tahun 2024. Namun, secara umum angka kemiskinan tiga kabupaten penghasil nikel itu justru meningkat dalam lima tahun terakhir. Di Bombana, jumlah penduduk miskin tercatat 18.840 jiwa pada 2020.
Sempat terjadi penurunan tahun 2022, tetapi jumlahnya meningkat lagi menjadi 20.560 jiwa pada 2024. Jumlah kemiskinan di Konsel juga mencapai 34.220 jiwa tahun 2020 dan 37.090 jiwa pada 2024. Angka kemiskinan di Kolaka pada 2020 juga tercatat 23.760 jiwa dan 33.200 jiwa tahun 2024.
Mengapa Kemiskinan Meningkat?
 Infografis alasan meningkatnya kemiskinan tiga daerah penghasil nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Desain: Chevin Breemer.
Infografis alasan meningkatnya kemiskinan tiga daerah penghasil nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Desain: Chevin Breemer.Ekonomi Sultra sebenarnya tumbuh konsisten dengan rata-rata 5,58 persen per tahun dalam rentang waktu 2013 hingga 2022. Penurunan signifikan sebesar -0,65 persen hanya terjadi pada 2020, karena gejolak pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan ekonomi selalu diikuti kualitas lingkungan yang menurun.
Dalam hipotesis Kurva Kuznet Lingkungan, ketika ekonomi meningkat pada titik puncak tertentu, seharusnya kerusakan lingkungan menurun seiring kesadaran masyarakat menjaga dan melindungi ekosistem daerahnya. Namun, Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, La Baco Sudia, menyebut pertumbuhan ekonomi di sektor sumber daya alam memang selalu menyisakan masalah.
Baco mengatakan pencemaran laut di Baliara dan hilangnya potensi rumput laut di Torobulu merupakan contoh amburadulnya pengelolaan lingkungan. “Teorinya begitu. Dalam pelaksanaan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang sumber daya alam, ada dokumen lingkungan yang disepakati. Kalau perusahaan patuh, sebenarnya tidak akan ada kerusakan lingkungan yang lebih parah,” kata Baco, Jumat, 25 April 2025.
 Infografis pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Desain: Chevin Breemer.
Infografis pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Desain: Chevin Breemer.Tata kelola lingkungan yang buruk menjadi awal masalah ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Menurut Baco, buruknya tata kelola lingkungan menyebabkan kerusakan yang dapat berdampak pada ekonomi hingga meningkatnya kemiskinan. “Kerusakan lingkungan itu berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan. Laut tercemar atau banjir pada lahan pertanian akan menurunkan produktivitas petani dan nelayan,” ungkapnya.
Bagi yang bekerja di sektor penambangan nikel, kerusakan lingkungan mungkin tidak berdampak secara langsung. “Namun, ketika misalnya dia mengonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi limbah timbal, itu akan menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat, misalnya,” jelas Baco.
Hal senada disampaikan Akademisi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan UHO Kendari, Caesar Muslim. Menurut Caesar, kerusakan lingkungan akibat tambang nikel dapat berdampak secara langsung terhadap kemiskinan, karena membuat petani serta nelayan butuh waktu beradaptasi mencari sumber penghidupan baru.
“Menurut saya tentu ada, meski butuh pembuktian empiris dengan penelitian lebih lanjut. Adanya pencemaran akibat aktivitas tambang nikel akan berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat lokal. Terlebih lagi mereka butuh waktu beradaptasi mencari sumber penghidupan baru,” kata Caesar, Senin, 21 April 2024.
Hasil penelitian Caesar Muslim pada tahun 2024 juga menunjukkan masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sultra. Meski angka kemiskinan Sultra turun dari 331.710 jiwa pada 2013 dan menjadi 309.790 jiwa tahun 2022, hal itu tidak mengatasi akar masalahnya.
Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan Sultra justru kembali berangsur naik dari 301.820 jiwa tahun 2020 menjadi 319.710 jiwa pada 2024. Penelitian Caesar menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak membantu mengurangi kemiskinan, melainkan malah memperparahnya. Menggunakan metode regresi linear sederhana, Caesar menyebut setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi di Sultra, kemiskinan juga naik 0,248 persen.
 Infografis jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bombana, Konawe Selatan (Konsel), dan Kolaka. Desain: Chevin Breemer.
Infografis jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bombana, Konawe Selatan (Konsel), dan Kolaka. Desain: Chevin Breemer.
Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kembali angka kemiskinan dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial dan politik, serta rendahnya pemerataan pendapatan masyarakat. Manfaat pertumbuhan ekonomi juga cenderung dinikmati golongan masyarakat tertentu.
Fenomena itu sejalan dengan teori kutukan sumber daya alam (natural resource curse) yang diperkenalkan Profesor Richard Auty dalam bukunya “Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis”. Penelitian Caesar berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Sulawesi Tenggara” juga sekaligus membantah teori trickle down effect. Teori itu menyebut pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tingkat kemiskinan, karena terciptanya kesejahteraan melalui investasi dan lapangan kerja. Namun, investasi pada sektor pertambangan nikel hanya dinikmati para cukong.
“Teori trickle down effect yang mengatakan setiap ekonomi tumbuh di suatu wilayah, semestinya menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian yang saya lakukan, malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonominya naik, tingkat kemiskinannya juga meningkat. Tentu itu karena tidak adanya pemerataan yang terjadi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, mengatakan masyarakat tingkat lokal sesungguhnya tidak benar-benar menikmati hasil eksploitasi nikel di daerahnya. Dia juga mencatat mayoritas pemilik izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Bombana, Konsel, dan Kolaka, berasal dari luar daerah, seperti Jawa, Kalimantan, bahkan warga negara asing (WNA) asal Cina.
Kepemilikan itu menyebabkan hasil eksploitasi kekayaan sumber daya alam cenderung dibawa ke luar daerah. “Kalau kita tracking, pemilik perusahaannya dari luar. Maka hasil kekayaan alam dari proses tambang itu juga akan dibawa ke luar. Kecuali misalnya di Kabaena, ada PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), itu punya Gubernur Andi Sumangerukka,” katanya, Kamis, 17 April 2025.
Penerima manfaatnya pun hanya elite di tingkat lokal dan orang yang dianggap mendukung penuh aktivitas pertambangan. Kenyataan itu makin diperparah ketika eksploitasi nikel malah mengganggu bahkan menghilangkan mata pencaharian masyarakat lokal yang bekerja sebagai petani dan nelayan.
Sementara mereka yang dilibatkan sebagai pekerja di sektor industri dan penambangan nikel hanya 15 sampai 20 persen. Di Baliara, masyarakat lokal yang bekerja di sektor pertambangan hanya 20 orang dari 1.442 jiwa total penduduknya. Masyarakat Desa Torobulu juga cuman 80 orang yang bekerja di sektor swasta seperti pertambangan dari 3.132 orang total penduduk.
Masyarakat Desa Okooko pun sama. Warga yang bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta berjumlah 110 orang dari 1.477 jiwa total penduduknya. “Masalahnya adalah yang dilibatkan hanya 15 sampai 20 persen, sedangkan wilayah penghidupan mereka malah dirusak,” ungkapnya.
Rencana Mengatasi Kerusakan Lingkungan di Sultra
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra, Andi Makkawaru, mengatakan wacana ekonomi berkelanjutan tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Salah satu poin Asta Cita juga masuk dalam program 100 kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka-Hugua, melalui program ekonomi berkelanjutan. “Ekonomi hijau ke daratan, ekonomi biru itu berarti ke wilayah lautan,” katanya, Selasa, 29 April 2025.
Untuk mendukung program itu, Pemprov Sultra akan menggunakan dana hibah di luar anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pada 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah menerima alokasi anggaran Rp2 miliar dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), unit organisasi noneselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dana tersebut akan digunakan Pemprov Sultra melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk tiga tahun ke depan. Selain pendanaan nasional, Pemprov Sultra juga menargetkan anggaran green climate fund (GCF), dana khusus global untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan menanggapi perubahan iklim.
“Ada pendanaan di luar APBN atau APBD yang tidak membebankan negara dan pemerintah. Apa itu? Dana perlindungan lingkungan hidup atau green climate fund. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai dipertajam dengan program REDD+ atau reducing emissions from deforestation and forest degradation,” tambahnya.
REDD+ dimaksud Andi Makkawaru adalah skema pendanaan global sebagai upaya mitigasi bencana deforestasi dan degradasi hutan yang disepakati melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992.
Selain itu, Pemprov Sultra akan mendorong pendapatan fiskal melalui pajak perusahaan pertambangan yang dinilai telah menyebabkan deforestasi dan mempercepat perubahan iklim. Menurut Andi Makkawaru, berbagai pendanaan tersebut akan menyasar masyarakat pesisir di Sultra yang dianggap kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim.
“Yang paling terdampak dari perubahaan iklim itu masyarakat pesisir. Kaya itu tadi, yang menambang di atas, kalau hujan limbahnya dibawa ke laut. Begitu terjadi badai, cuaca tidak pasti, pasang surut tidak jelas, maka yang terkena adalah masyarakat pesisir,” jelasnya.
Namun, Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman, mengaku pesimis dengan wacana ekonomi berkelanjutan tanpa mendorong transisi energi dari mineral kritis. Dia mencontohkan hilirisasi nikel di Sultra, sebuah program pengoptimalan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tujuan hilirisasi nikel tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan sejak awal. Pelbagai dampak buruk justru muncul akibat program tersebut, seperti meningkatnya kemiskinan daerah penghasil nikel, menurunnya kualitas lingkungan, dan kriminalisasi masyarakat sipil yang memberi kritik.
“Siapa tidak sepakat dengan tujuan kebijakan hilirisasi nikel soal kesejahteraan yang akan meningkat? Konsepnya kita terima dan saya kira bagus. Namun, saya pesimis, karena praktiknya selalu berbanding terbalik dengan apa yang direncanakan,” ungkapnya.
Dosen Ilmu Lingkungan UHO Kendari, La Baco Sudia, menyebut Indonesia akan benar-benar beralih dari mineral kritis ke energi bersih jika dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar nyata terjadi. “Wacananya bagus dan mungkin kita akan ke sana. Namun, kita di Indonesia kejadian dulu baru melakukan tindakan. Kita perlu ingat, pemulihan kerusakan lingkungan itu sangat mahal,” ujarnya.
Artikel ini merupakan serial liputan yang didukung penuh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Traction Energy Asia melalui program Akademi Jurnalis Ekonomi-Lingkungan (AJEL) Tahun Ke-3.
Post Views: 59

 1 month ago
49
1 month ago
49







































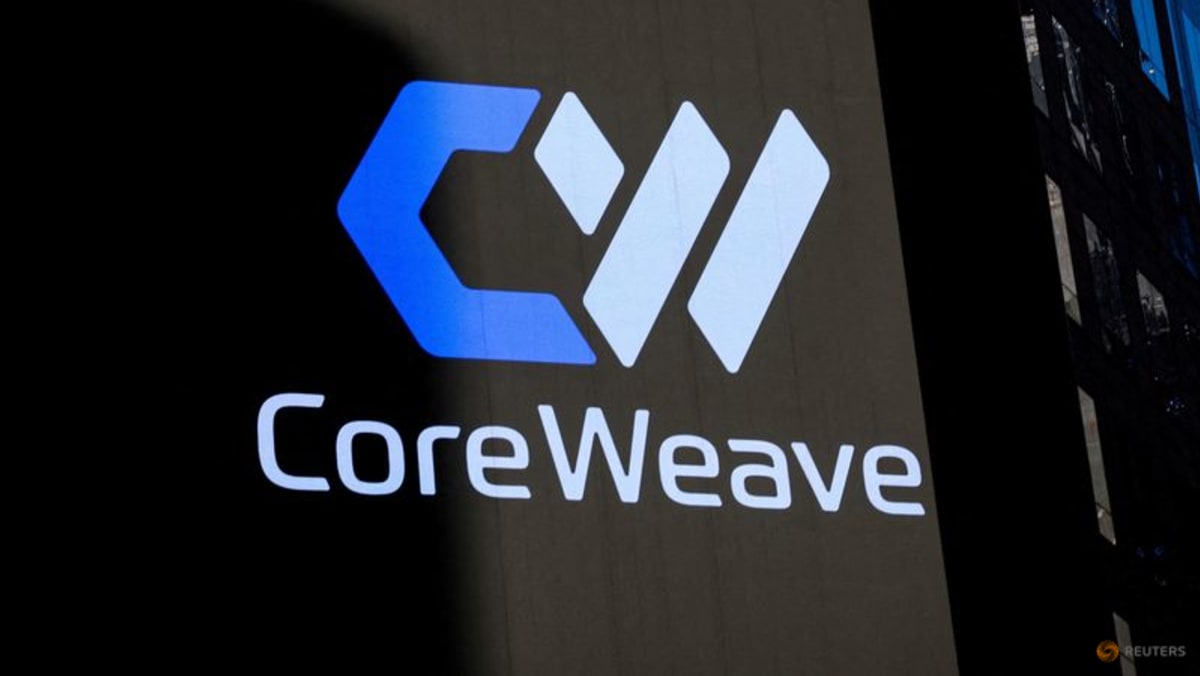








.png?itok=erLSagvf)
