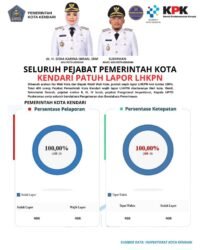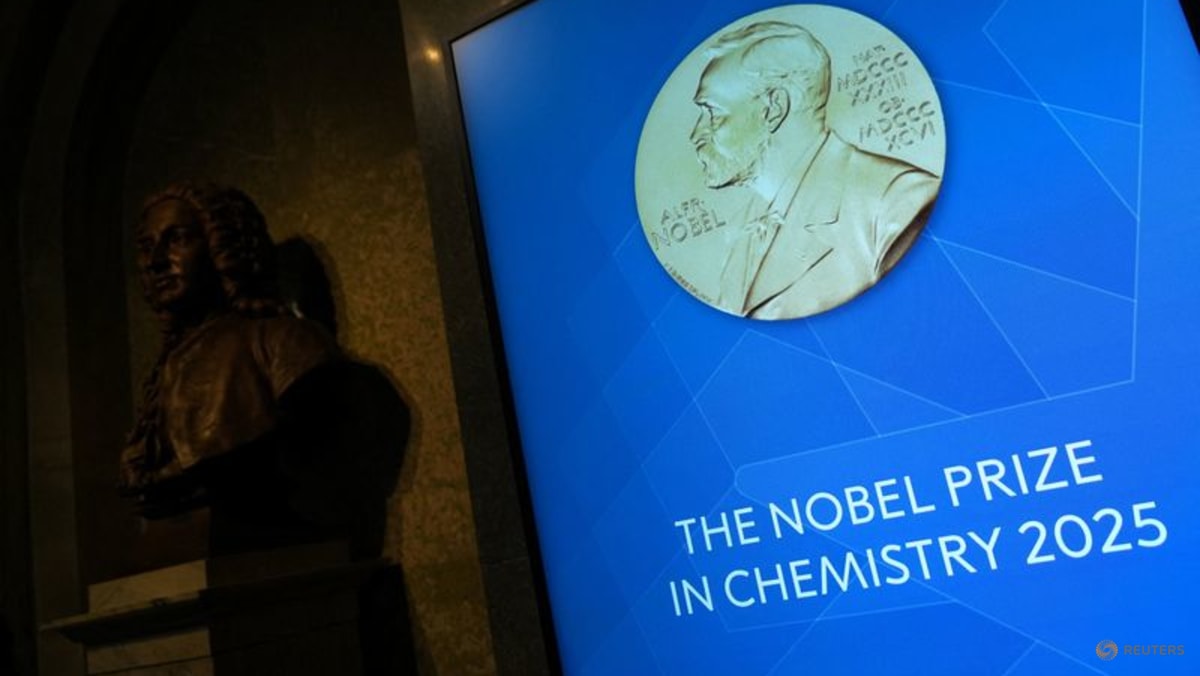Belakangan, linimasa media sosial diramaikan dengan seruan boikot terhadap stasiun televisi Trans7. Tayangan yang menyorot aktivitas sisi lain dunia pesantren yang dianggap melecehkan kiai, santri, dan lembaga pesantren secara umum. Banyak tokoh agama dan alumni pesantren bereaksi keras, mereka menilai program dengan tema “Xpose Unsensored” itu telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam tradisional.
Sebagai alumni pesantren selama tiga tahun, saya justru melihatnya dari sisi berbeda. Tayangan itu memang keliru dalam narasinya yang menggeneralisasikan semua pesantren, tetapi tidak sepenuhnya salah dalam melihat realita. Fakta bahwa ada pesantren yang menerapkan disiplin keras dengan dalih “mencari berkah” bukanlah hal baru. Beberapa pesantren memang punya tradisi pendisiplinan yang keras dan itu layak dikritisi.
Ruang pendidikan, termasuk pesantren, seharusnya terbuka terhadap kritik. Justru dari kritiklah lembaga bisa memperbaiki diri. Yang perlu dikritik bukan keberadaan kritik itu sendiri, tapi cara media membangun narasi. Jika Trans7 salah, maka yang salah adalah generalisasi dan potongan visual yang tidak merepresentasikan semua pesantren, bukan karena berani membicarakan isu sensitif.
Di kalangan santri, ada istilah populer: “Penjara Suci” istilah ini bukan sindiran, melainkan refleksi. Santri menyebut pesantren demikian karena tempat itu menjadi ruang “penyucian diri” melalui berbagai bentuk hukuman atau disiplin dari kiai dan ustaz. Namun, dalam praktiknya, doktrin “berkah” kadang dijadikan pembenaran bagi tindakan-tindakan berlebihan, bahkan yang sifatnnya dehumanisasi (tak manusiawi).
Lebih jauh, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di beberapa pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan tempat suci yang bebas dari kesalahan manusia. Kiai, gus, ustaz, dan pengurus pondok juga manusia biasa yang bisa salah dan harus bisa dikoreksi.
Martin van Bruinessen, seorang antropolog yang lama meneliti pesantren, menyebut bahwa otoritas kiai dalam tradisi pesantren kerap mendominasi sehingga santri sulit bersikap kritis terhadap guru mereka, istilah ini ia sebut sebagai Culture of Obidience. Meski kiai berperan penting dalam menjaga nilai-nilai Islam tradisional, kata Bruinessen, “ketundukan total tanpa ruang dialog adalah problem lama dunia pesantren”.
Sementara itu, Azyumardi Azra dalam bukunya “Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru” menilai bahwa pesantren perlu melakukan transformasi epistemologis, yaitu membuka diri terhadap ilmu-ilmu modern dan pendekatan baru dalam pendidikan. Menurutnya, pesantren yang menutup diri terhadap perubahan akan sulit beradaptasi dengan tantangan zaman.
Bahkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga lahir dan besar di tradisi pesantren, pernah mengingatkan bahwa “pesantren harus tetap berpijak pada tradisi, tapi tidak anti modernisasi”, Dalam pandangannya, cinta terhadap pesantren tidak berarti menutup mata terhadap kesalahannya. Kutipan ini bisa diakses pada buku Pesantren sebagai subkultur yang terbit 1988.
Saya jadi teringat ucapan ustaz saya dulu:
“Pesantren itu bukan bengkel, yang kalau anak dari luar nakal lalu dimasukkan ke pondok bisa langsung jadi baik”.
Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Banyak orang tua masih memandang pesantren sebagai tempat perbaikan moral instan. Padahal, realitanya tak sesederhana itu. Di pondok pun, kita sering mendengar kasus pencurian, pembulian, bahkan pelecehan. Santri juga manusia, dan pesantren juga bagian dari masyarakat lengkap dengan sisi gelap dan terangnya.
Karena itu, mengkritik pesantren bukan bentuk kebencian terhadap Islam, melainkan bagian dari kepedulian agar pesantren tidak kehilangan jati dirinya. Pemikiran seperti ini sejalan dengan pandangan Mansour Fakih, yang menyebut bahwa pesantren seharusnya menjadi arena pemberdayaan sosial yang egaliter, bukan sekadar reproduksi otoritas keagamaan. Dominasi kiai dan hierarki di dalamnya tidak boleh menghapus ruang dialog dan kritik.
Lalu, mengapa ketika pesantren dikritik, sebagian dari kita langsung marah? Bukankah kritik adalah tanda perhatian dan cinta terhadap lembaga yang kita banggakan? Justru dari kritiklah pesantren bisa menjadi tempat yang lebih baik, lebih terbuka, lebih manusiawi, dan lebih mendidik.
Tayangan Trans7, menurut saya, tidak sepenuhnya keliru, hanya kurang cermat dalam memotret realitas pesantren secara komprehensif. Reaksi berlebihan justru menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan pesantren sebagai ruang sakral yang tabu dikritik. Padahal, jika pesantren ingin terus dipercaya publik, ia harus siap berbenah dan terbuka terhadap evaluasi.
Akhirnya, saya menulis ini bukan untuk menyudutkan siapa pun, tetapi sebagai seseorang yang pernah bergumul di dunia pesantren, juga sebagai masyarakat yang mencintai lembaga itu. Pesantren tetap tempat mulia, tapi bukan tempat suci yang kebal kritik. Karena yang suci hanyalah Tuhan bukan lembaganya. Namanya juga manusia, bukan Nabi boy.
Opini: Penulis, Akademisi, dan Da’i, Ibnu Azka
Post Views: 43

 3 months ago
87
3 months ago
87