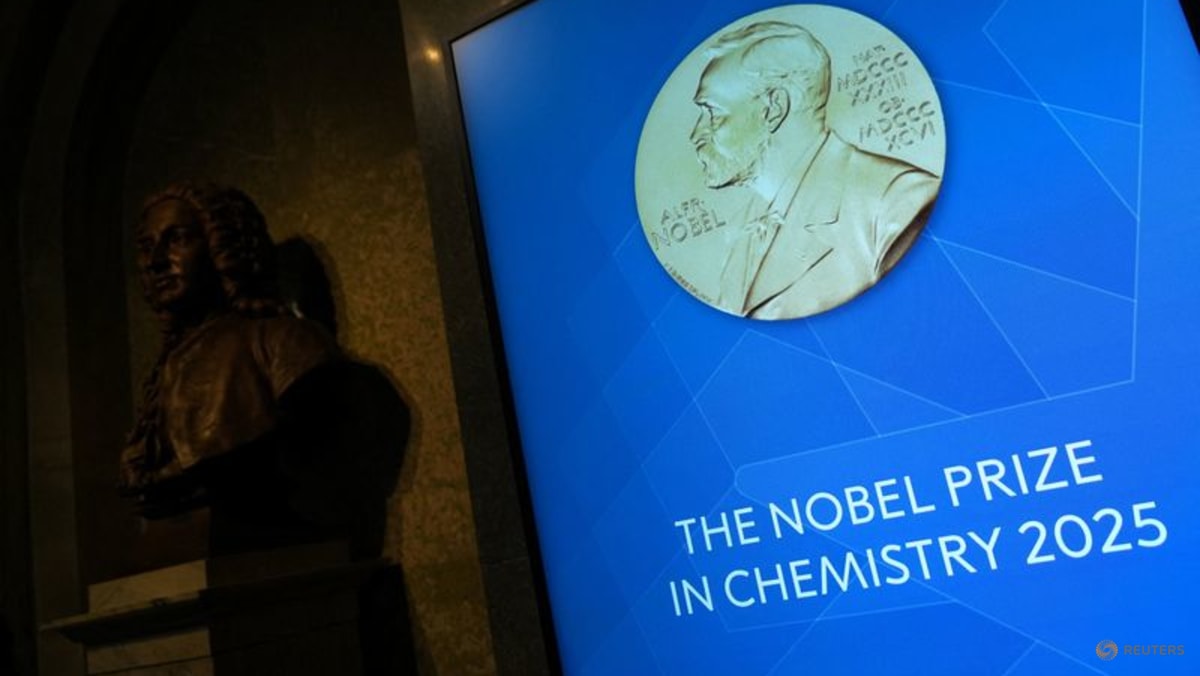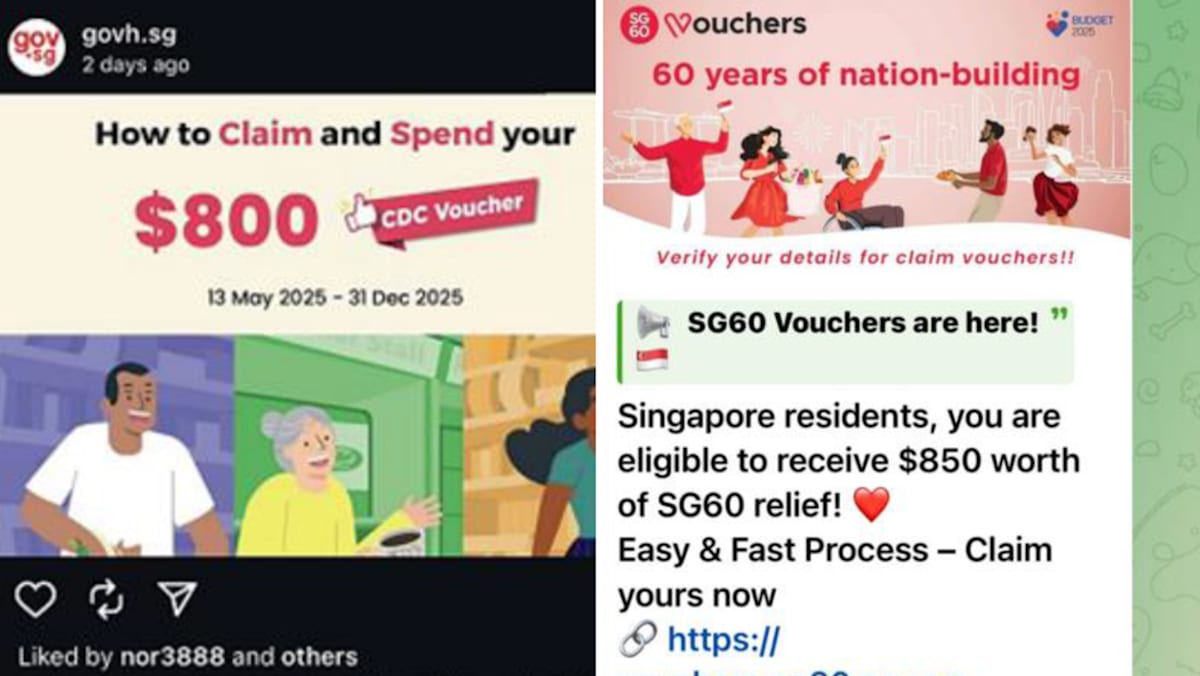Sulawesi Tenggara – Perlawanan masyarakat di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar), dari kerusakan lingkungan perlu berkaca dengan yang terjadi di Wawonii dan Kabaena, Sulawesi Tenggara (Sultra). Jika Pulau Sipora masih dalam ancaman ekspansi hutan PT Sumber Permata Sipora (SPS), Wawonii dan Kabaena telah merasakan tanda-tanda ekosida akibat aktivitas penambangan nikel.
Cerita itu diungkap dalam diseminasi hasil liputan investigasi kolaborasi bertajuk “Menyelamatkan Mentawai dari Keserakahan” yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Simpul Sultra, Minggu (28/9/2025). Diskusi itu diikuti jurnalis lingkungan di Kendari, pers mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.
Diskusi yang diawali nonton bareng itu dipandu Jurnalis CNN Indonesia TV, Zainal A. Ishaq. Pemantik dalam diskusi ialah Jurnalis Ekuatorial, Febriyanti; Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Andi Rahman; Akademisi Hukum Universitas Halu Oleo (UHO), Sahrina Safiuddin, dan Jurnalis Kabarkendari.id, Randi Ardiansyah.
 Peserta diseminasi hasil liputan investigasi kolaborasi bertajuk “Menyelamatkan Mentawai dari Keserakahan” yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Simpul Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Istimewa. (28/9/2025).
Peserta diseminasi hasil liputan investigasi kolaborasi bertajuk “Menyelamatkan Mentawai dari Keserakahan” yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Simpul Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Istimewa. (28/9/2025). Febriyanti yang merupakan bagian dari liputan investigasi menyebut Kepulauan Mentawai sebagai Galapagos Asia di Indonesia, karena memiliki keragaman hayati, satwa endemik, dan primata. Namun, satwa endemik perlahan berkurang, karena aktivitas perburuan liar.
Jika PT SPS melakukan eksploitasi dengan menebang pohon, satwa endemik di Pulau Sipora benar-benar akan punah. Febriyanti juga menyayangkan keberpihakan pemerintah kepada perusahaan. Ia mengatakan pemerintahan mengabaikan keresahan masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aktivitas PT SPS.
“Pemerintah bukan justru melindungi pulau dan menyelamatkan seluruh makhluk di atasnya, melainkan menerbitkan izin baru untuk perusahaan. Kita tahu, salah satu primata di Sipora merupakan bagian dari 25 primata terancam punah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu perhatian dan perlawanan dari semua elemen masyarakat, masyarakat sipil dan kolaborasi para jurnalis,” katanya.
Jurnalis CNN Indonesia TV, Zainal A. Ishaq, yang juga merupakan warga Pulau Kabaena mengungkapkan perusahaan di Pulau Sipora hanya mengambil di atas tanahnya. Namun, jika di Sultra, tanah pun digali lalu dibawa ke luar daerah. Zainal bilang kerusakan lingkungan telah terjadi di beberapa daerah Sultra, seperti Morombo, Konawe Utara (Konut); Kabaena, Bombana; serta Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan; disebabkan industri ekstraktif yang masif merusak lingkungan.
“Kalau di Sultra di bawah tanah pun ditambang, diambil dibawa ke luar. Sultra ini jadi pelumas politik di Jakarta,” ungkap Zainal.
Berdasarkan data Satya Bumi dan Walhi Sultra, area izin usaha pertambangan (IUP) di Kabaena telah mencakup sekitar 73 persen total luas pulau atau 650 kilometer persegi dari total 891 kilometer persegi. Angka itu menunjukkan sebagian besar pulau telah dialokasikan untuk izin perusahaan tambang nikel.
Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) melarang tambang di pulau kecil yang luasnya kurang 2.000 kilometer persegi. Di Pulau Kabaena, masyarakat suku Bajo telah kehilangan tradisi, seperti memancing dan menyelam. Air lautnya keruh sepanjang tahun ditutupi sedimentasi lumpur yang berasal dari aktivitas tambang.
“Kalau pun memancing di tempat lebih jauh, biayanya mahal. Mereka tidak bisa lagi memancing, beralih kumpul-kumpul ikan dari nelayan lain lalu dijual kembali untuk bertahan hidup,” ujar Zainal.
Menurut Zainal, masyarakat di Kabaena sebenarnya pernah berjuang keras mengusir perusahaan tambang. Akibat penolakan itu, tak sedikit masyarakat yang dilaporkan ke polisi dan berujung penjara. Namun, karena pendekatan perusahaan, warga berbalik mendukung. Orang-orang yang pernah dipenjara bahkan berbalik menjadi pelaku dan pemain tambang.
“Tidak ada orang yang berani lawan polisi, kecuali warga Kabaena. Sampai 10 orang masuk penjara, jauh sebelum orang Wawonii dipenjara. Begitu pula proses perlawanan di Wawonii sebenarnya. Orang-orang yang melawan perlahan direkrut lalu dibenturkan sesama mereka,” kata Zainal.
Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman, mengungkap hasil penelitian bersama Satya Bumi di Pulau Kabaena. Ia mengungkapkan anak-anak di Pulau Kabaena sudah terkontaminasi kandungan nikel di tubuh mereka yang ditemukan dalam urin.
“Kandungan nikel itu berasal dari air dan ikan yang mereka konsumsi. Jadi sudah sejarah itu kerusakannya. Bahwa, di Sipora baru bicara ancaman, di Sultra sudah merasakan kerusakan ekologis,” ungkap Andi.
Kendati demikian, Andi memuji kesadaran yang ditunjukkan masyarakat adat dan pemerintah desa di Pulau Sipora terkait ancaman eksploitasi hutan. Menurutnya, konsistensi itu harus dirawat dan dijaga agar tidak tergoda propaganda perusahaan dengan iming-iming kesejahteraan serta lapangan kerja, sebagaimana di Pulau Wawonii.
Andi bilang, di Pulau Wawonii, akibat pendekatan dengan politik pecah belah perusahaan, warga yang awalnya menolak keras masuknya tambang jadi pendukung bahkan provokator. Kondisi itu juga dimanfaatkan pemerintah dengan dalih pembangunan dan ekonomi, sehingga membuat pena kebijakan serta memberikan izin kepada perusahaan tambang.
Padahal jelas-jela Undang-Undang PWP3K melarang adanya aktivitas tambang di Pulau Wawonii. Andi juga mengkritisi arah kebijakan pemerintah yang salah kaprah bahkan keliru. Dia menilai pemerintah terlalu mengandalkan industri ekstraktif yang merupakan ekonomi semu dan hanya dinikmati segelintir orang.
“Tidak ada daerah yang kaya karena tambang. Yang ada pelanggaran HAM naik dan kemiskinan meningkat. Kalau pemerintah berpikirnya ekonomi berkelanjutan, lau dijaga, pertanian dirawat, saya yakin ekonominya meningkat dan anak cucunya akan menikmati,” ungkapnya.
Akademisi Hukum Lingkungan UHO Kendari, Sahrina Safiuddin, melihat ancaman kerusakan lingkungan di Pulau Sipora dan beberapa daerah di Sultra disediakan konstitusi. Sahrina menjelaskan konstitusi mengatur dua hal, yakni sebagai perlindungan hak asasi manusia (HAM), seperti Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan instrumen ekonomi.
“Dalam perkembangannya, ketika revisi UUD 1945, Pasal 33 itu semangatnya bernuansa ekonomi liberal yang semuanya tergantung pada pasar,” ungkapnya.
Sahrina mencontohkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai lex generalis. Undang-undang itu diatur sebagai anti-SLAPP (strategic lawsuit against public participation) untuk melindungi warga negara yang memperjuangkan lingkungan baik dan sehat.
Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) justru dapat memidanakan orang yang menghalangi aktivitas pertambangan. Aturan yang bersifat sektoral harusnya merujuk pada aturan lex generalis, seperti Undang-Undang PPLH.
“Di Undang-Undang PPLH disebutkan orang yang memperjuangkan lingkungan hidupnya tidak boleh dipidana. Di undang-undang minerba yang baru, menghalangi aktivitas pertambangan bisa dipidana. Jadi secara norma sudah berbenturan. Akhirnya penegakan hukum bukan lagi soal keadilan dan kemanfaatan, tetapi pada political will,” tandasnya.
Post Views: 87

 3 months ago
96
3 months ago
96